Sekolah YPK di Papua: Sejarah Singkat Pendidikan Di Kepala Burung.
Sekolah YPK di Papua: Sejarah Singkat Pendidikan di Kepala Burung.
________________________________
Papua No 1 News Portal | Jubi ,
pacefanindi.blogspot.com
__________________
Oleh: Kris Ajoi 🙋♂️
Orang Papua semestinya berterima kasih kepada gereja dan pendidikan yang dibangun melalui gereja. Untuk itu dalam rangka memperingati lahirnya YPK di Papua, semestinya semua orang Papua pantas merefleksi kembali untuk memahami jalan cerita pendidikan yang dipelopori oleh zending yang kemudian melahirkan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan misionaris Katolik yang memprakarsai lahirnya Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK).
Kedua lembaga itu telah berjasa membangun peradaban lewat sekolah-sekolah dan pendidikan dalam bidang lain meliputi etika, keagamaan dan praktek kejuruan.
Sejarah pendidikan di Papua tidak terlepas dari peranan zending dan misi Katolik. Peran yang fokus terhadap penanaman karakter pendidikan yang memanusiakan manusia Papua pada umumnya dan terlebih mempersatukan. Kemudian pembangunan itu membentuk identitas pendidikan Papua sesuai kultur kebudayaan lokal sehingga orang Papua dan semua orang luar dapat melihat pendidikan Papua dari sejarah dan model pendidikannya.
Sejarah pendidikan Papua berkembang lewat beberapa fase. Fase budaya, fase gereja, dan fase pemerintahan dengan lembaganya masing-masing. Dapat pula ditambahkan adanya campur tangan perusahaan dalam proses pembangunan fisik dan dukungan dana. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa proyek triple G yang dibawa oleh para pendatang Eropa adalah modus pengadaban dan penguasaan yang disebut dengan Gold (Emas), Gospel (Alkitab/Injil), dan Glory (Kejayaan/Suatu Kekuasaan). Sekaligus memperlihatkan model pendidikan yang dapat dilihat dari pendidikan adat (inisiasi) dan pendidikan adat formal sebagaimana sekolah sekarang. Dengan demikian tidak bisa dikesampingkan bahwa sejarah pendidikan terpisah dari proses sejarah yang lain, karena pendidikan, gereja, adat dan pemerintah membangun bersama, saling mengisi dan berkaitan.
Papua Barat di dalam sejarah dikenal sebagai wilayah yang lebih dahulu disinggahi para pelaut asing dari Barat. Baik pelaut Portugis, Inggris, Belanda maupun Indonesia. Wilayah pantai utara dikenal dengan Teluk Cenderawasih. Wilayah selatan dikenal dengan semenanjung Onin yang mempertemukan penduduk Fakfak, Kaimana, Babo, Arandai, Agats, Kokonao, hingga Merauke. Penduduk Mek (Mee/Ekagi) dan Amungme yang dikenal sebagai masyarakat yang mendiami pegunungan dapat bertemu dengan penduduk Asmat dan Kamoro. Begitu pula bertemu dengan penduduk Fakfak dan Kaimana. Di wilayah utara, penduduk pegunungan Arfak termasuk penduduk Mpur juga mengunjungi daerah pesisir di Manokwari untuk mencari pengalaman dengan terlibat dalam perubahan bersama dengan penduduk Kuri-Wamesa, pesisir Teluk Wondama, Biak-Numfor, Roon, Warbefor hingga Manokwari pesisir.
Khusus di wilayah Kepala Burung yang tadi disebutkan itu hubungan budak dan kain timur, hubungan pengayauan dan perompakan, budak dan perdagangan cenderawasih, porselin, kain dan masih banyak lagi hubungan yang membentuk suatu relasi kuat dan menghidupkan jaringan sosial.Ditambah dengan perkawinan sebagai pengikat yang sah.
Orang Papua di Kepala Burung mulai merasakan betapa nikmatnya perubahan yang datang setelah melalui pendidikan. Tanah yang luas dan penduduk yang sedikit dengan pikiran yang terbelenggu di dalam ikatan sosial-budaya yang kadang mengalami peningkatan hubungan baik. Namun, kadang dihiasi dengan konflik-kekerasan berkepanjangan menandai suatu kebudayaan Papua yang hidup.Yang berbeda dengan itu adalah arus perubahan itu memberikan tekanan pada keadaan orang Papua yang cenderung dalam pandangan orang lain (outsiders) dicap sebagai malas dan bodoh. Alhasil, orang Papua menerima justifikasi yang tidak sedikit dari penduduk pendatang dan arus perubahan yang diiukutsertakan di dalamnya.
https://jubi.co.id/sekolah-ypk-di-papua-sejarah-singkat-pendidikan-di-kepala-burung/amp/
https://pacefanindi.blogspot.com/Bicaramampap
Namun khusus untuk pendidikan dalam tradisi budaya Papua itu juga tidak kalah. Beberapa orang tua di wilayah Kampung Senopi berceritera tentang Rae Wuon dan Fenia Meroah yang dilakukan di Wuon Akasikos (rumah para pria) dan Fenia Mekiar (rumah para wanita). Mereka belajar memahami hakikat hidup manusia dan mendalami filsafat hidup antara kenyataan esensial tentang keberadaan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam. Terlebih lagi memahami suatu maksud di balik keadaan manusia yang tidak dapat dimengerti selain dari “Sang Pemberi Hidup”. Samuel Bless dan Bernad Baru dalam kesempatan yang berbeda menyatakan bahwa di tempat ini orang-orang belajar memahami dunia dengan cara “dipaksa untuk menguasai segala sesuatu yang bisa dikuasai maupun yang tidak bisa dikuasai” (Bless, 2018) dan mengerti maksud Tuhan (Baru, 2013).
Bicara soal pendidikan atau sekolah formal tentu berbeda, YPPK di Kepala Burung dimulai dari Fakfak hingga Tintum-Tabamsere, Maret 1949 kemudian pembukaan pos pendidikan terpusat di Kampung Senopi, Ayata, Suswa, Ayawasi-Konja dan Moskona dan Babo hingga SMA yang terpusat di Sorong, yaitu SMA Santo Agustinus. Sekarang YPPK telah memperluas karyanya mendidik anak-anak Papua melalui berbagai misi pelayanan terutama di dalam ordo.
Di Kepala Burung, ordo yang paling berkenaan di hati masyarakat karena pendidikan ialah Ordo Santo Agustinus (OSA)—sebelumnya OFM/Ordo Fratrum Minororum pernah ada juga di daerah selatan Kepala Burung, yang memprakarsai pendidikan di beberapa wilayah tadi dengan sedikit bantuan dari NNGPM, sebuah perusahaan minyak dan gas yang telah beroperasi di Sele, Sorong dan Babo sejak 1930-an (Tromp, 2013).
Untuk zending sendiri, awalnya kesadaran untuk mendirikan sekolah datang dari Nyonya Ottow, memperlihatkan bahwa peran perempuan lebih dominan dalam mendidik anak. Ia membuat sekolah di sebuah bilik di rumahnya. Mereka menebus budak-budak dan memasukkan para budak di sekolah dan dididik bersama-sama. Meski dalam tahun-tahun itu terjadi berbagai masalah dari penyakit hingga konflik internal yang berujung pada kepergian Ottow pada 1957 ke Kwawi untuk membangun pos di sana, sekolah dijadikan sebagai tempat untuk mendidik, sekolah terus bertumbuh. Tapi apa daya lagi, tahun 1875 sekolah itu ditutup karena adat yang mengharuskan perempuan dan laki-laki tidak boleh digabung. Sekolah ini tidak dapat disangkal berasal dari niat para Zending yang datang berturut-turut. Awalnya Zending Werkleden (Utusan Tukang) tahun 1849 dan sampai 1855 (Ottow dan Geissler), disusul Netherlands Zendeling Genootschap (NZG Belanda) 1858, dan kemudianUltrechtse Zendeling Vereningin (UZV Belanda) 1859. UZV yang melanjutkan kegiatan zending di Kepala Burung membuka sekolah di Mansinam, Teluk Doreri. Setelah F.J.F van Hasselt tiba di Mansinam untuk bertugas pada tahun 1863 yang sekaligus menandai masuknya UZV itu, ia memperbaharui pendidikan dengan membuka sekolah guru di Mansinam tahun 1917.
Sekolah di masa UZV semakin bertambah dan terutama pada pos-pos penginjilan di wilayah pantai utara dari Andai sampai ke Miei di Wasior, Jende (Pulau Roon), Biak-Supiori, ke Selatan, Fakfak dan ke timur di Tanah Tabi, semua berlangsung pada periode 1863-1907.
Sebagai usaha lanjutan, para zending mengirim para generasi Papua yang telah mendapat bekal di sekolah Papua untuk belajar lagi di luar Papua, tepatnya di Depok pada Kweekschool. Hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan guru melalui guru-guru pribumi yang berhasil sekolah, karena guru-guru masih didatangkan dari daerah Maluku untuk membantu pekerjaan pendidikan di Papua. Mengingat pada tahun 1607 di Ambon telah didirikan sekolah pertama oleh VOC kemudian sekolah di beberapa wilayah kepulauan yang menjadi basis bisnis VOC dibangunlah juga sekolah-sekolah (Nasution, 2008: 4).
https://jubi.co.id/sekolah-ypk-di-papua-sejarah-singkat-pendidikan-di-kepala-burung/amp/
https://pacefanindi.blogspot.com/Bicaramampap
Mereka yang beruntung pada generasi pertama ini dalam dua gelombang pengiriman adalah Petrus Kafiar dan Timotius Awendu kemudian Johan Ariks, W. Rumainum, J. Rumfabe, K. Koibur, dan J. Sorawan. Begitu terus hingga para generasi muda Papua ini kembali mengabdi menjadi guru dan pengajar alkitab di Papua. Mereka dibagi ke tempat tugas di wilayah Kepala Burung Papua. Johan Ariks diketahui bertugas di Andai, Momi Waren, Wondama kemudian bersama dengan I.S. Kijne setelah sekolah guru di Mansinam dipindahkan oleh F.J.F. van Hasselt tahun 1925 ke Miei (Wamea,D, 2010: 36), sampai dengan lahirnya generasi Miei seperti Bapak Tom Wospakrik, termasuk F.J.S Rumainum yang menjadi ketua sinode GKI pertama pada tahun 1956 (28 Oktober).
Setelah itu pada tanggal 8 Maret 1962 para pekerja gereja dan guru-guru yang bertugas di Papua ini mendirikan sebuah lembaga yang bertugas mengurus sekolah gereja di Papua yang diberi nama Yayasan Pendidikan Kristen (Wamea, D., 2010:31-36). Di wilayah pegunungan Arfak, daerah yang mayoritas diisi oleh sekolah YPK adalah wilayah suku Mpur di daerah Kebar Tambrauw.
Setelah injil masuk tahun 1947, sekolah rakyat diganti dengan sekolah YPK di Inam, kemudian dibuka sekolah dasar di Anjai. Sempat terjadi konflik ketika Soeharto ingin mengganti sekolah ini menjadi sekolah Inpres (Instruksi Presiden) namun hal itu tidak terjadi karena kuatnya protes dari gereja dan para guru YPK di Kebar. Salah seorang alumnus Miei, Bapak Kambu yang pernah bertugas di Kebar menceritakan kisahnya ketika bertugas di SP Manokwari dan harus meninggalkan tempat tugas dalam waktu singkat ke Kebar untuk membangun sekolah. Penolakan tidak mungkin mereka lakukan karena karena karakter mendidik dan pemahaman mereka terhadap arti penting sekolah di Papua. Wempi Kambu sampai di Kebar dengan pesawat dan mulai bekerja membangun masyarakat Mpur di Kebar dengan membangun SD YPK Anjai, setelah itu menyusul SMP Negeri 9. Di Teminabuan pada 1911, zending telah melakukan perjalanan pekabaran injil di sana. Begitu pula di daerah Ayamaru dan Aitinya yang berbatasan dengan penduduk Katolik di Aifat Raya dan penduduk Miyah (Karon) yang berbatasan dengan suku Mpur.
Proses penyebaran agama yang tidak terlepas dari konflik dan persaingan itu tidak memberhentikan gagasan untuk terus mendidik orang Papua agar hidup. Etika dan kebudayaan menjadi bagian dari upaya penguatan yang dilakukan oleh para zending saat pengajaran dan penginjilan dilakukan. Sayangnya, para zending lebih mengutamakan injil sehingga beberapa nilai kebudayaan yang melahirkan etika bagi pemilik budaya itu ikut hilang. Beberapa di antaranya dibakar, atau ditenggelamkan di air laut, danau atau sungai. Berbeda dengan para misionaris Katolik yang melindungi kebudayaan ini untuk dipelajari dan diasimilasikan dengan injil untuk menjadi model pendidikan di sekolah berbasis asrama yang masih terlihat hingga saat ini.
Saat perubahan itu terjadi, kontak-kontak penduduk tidak hanya dengan materi yang dihubungkan dengan struktur kebudayaan masyarakat. Pengembangan pengetahuan juga ikut diperkuat di sana melalui pendidikan. Sekolah zending dan model pendidikan misi mula-mula memang sulit masuk dan menyatu dengan budaya Papua. Namun, selepas beberapa fase kemudian sekolah ini mulai mendapat perubahan positif. Hal itu terjadi karena para zending dan misi mempelajari suatu hubungan yang sulit. Sehingga bukan perubahan mindset alami penduduk Papua yang diubah dengan Worldview yang dibawa dari Eropa, melainkan usaha untuk mendidik dengan cara sebagaimana orang Papua dididik.
Hal ini membantu para zending dan misi dalam mengolah pendidikan di Tanah Papua. Pola mendidik anak Papua yang diharuskan dengan tatap muka merupakan hal yang membuat para pendidik itu tinggal di Papua sampai bertahun-tahun. Mereka rela meninggalkan sanak-saudara untuk membangun Papua (menyangkal diri), menderita sakit dan wabah yang menimbulkan kematian bahkan semakin memperkuat tekad mereka untuk tetap tinggal dan mengabdi di Tanah Papua. Tujuannya untuk menyatu dengan budaya orang Papua dengan belajar bahasa dan memahami nilai budaya dalam kepercayaan penduduk yang paling hakiki.
Lukisan pengalaman mengenai pendidikan di Tanah Papua itu menjadi suatu kenyataan bahwa sekolah diyakini menjadi pintu bagi kemandirian orang Papua. Dengan cara itulah mulai diperdengarkan cerita mengenai “kota emas” yang harus dipimpim oleh penduduk itu sendiri sehingga mereka dikatakan “Tuan di Negeri Sendiri”. Sayang sekali cerita itu hampir seperti “ombak yang tidak pernah mencapai pantai” karena model pendidikan yang sangat riskan, bahkan jauh dari harapan, lalu bagaimana dengan Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua? (*)
Penulis adalah alumnus STPMD “APMD”
TAG:
▪︎ https://pacefanindi.blogspot.com
▪︎ Bicaramampap https://jubi.co.id/sekolah-ypk-di-papua-sejarah-singkat-pendidikan-di-kepala-burung/amp/
Forwarded By: 👤 Eckber














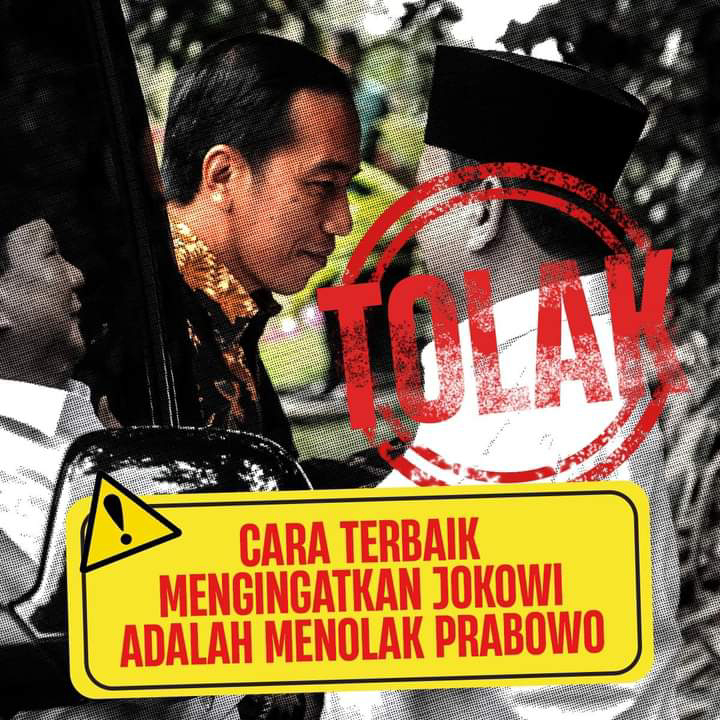
Komentar
Posting Komentar